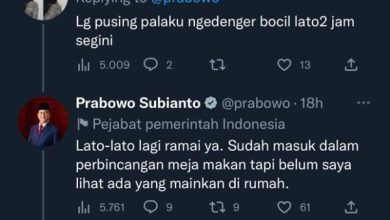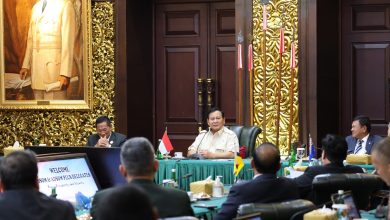BIMATA.ID, JAKARTA- Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo berjanji untuk mengejar produksi kedelai lokal dalam waktu 200 hari atau dua kali musim tanam. Ini merupakan upaya untuk mengatasi lonjakan harga tempe dan tahu beberapa waktu terakhir.
Tercatat, harga kedelai di pasar internasional naik 9 persen dari kisaran US$11,92 menjadi US$12,95 per busel. Alhasil, harga kedelai impor yang dibeli Indonesia sebagai bahan baku tahu tempe naik dari kisaran Rp9.000 menjadi Rp9.300 per kilogram (kg).
Indonesia memang masih amat bergantung dengan kedelai impor. Hal ini khususnya produsen atau pengrajin tahu dan tempe yang membutuhkan kedelai impor sebagai bahan baku.
Akibatnya, biaya produksi tahu dan tempe ikut naik ketika harga kedelai impor melonjak. Sebagian pengrajin tahu dan tempe sempat menaikkan harga tahu dan tempe sebesar 20 persen-30 persen, tapi sebagian lagi mencoba mempertahankan harga agar dagangannya laku.
Namun, lama-kelamaan mereka yang mempertahankan harga rugi lantaran harga kedelai impor semakin mahal. Untuk itu, pengrajin tahu dan tempe sempat melakukan aksi mogok produksi pada 1-3 Januari 2021 lalu sebagai bentuk protes atas harga kedelai impor yang tinggi.
Ini menjadi polemik besar di Tanah Air. Maklum, mayoritas masyarakat Indonesia kerap menjadikan tahu dan tempe sebagai “hidangan wajib” di meja makan.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menilai upaya pemerintah untuk menggenjot produksi kedelai dalam 200 hari di dalam negeri tak akan berhasil. Impor kedelai tetap akan tinggi seperti sebelum-sebelumnya.
“Tidak akan bisa, pasti gagal. Upaya swasembada kan sudah dari dulu, kenyataannya impor kedelai naik terus,” tutur Dwi.
Berdasarkan catatannya, total impor kedelai pada 2014 sebanyak 4,2 juta ton. Lalu, jumlahnya naik mencapai 7,2 juta ton sepanjang 2019.
“Jadi kalau mau ekstensifikasi (perluasan lahan) ya jawabannya pasti gagal, karena contoh banyak, sudah pernah, sama saja,” ucap Dwi.
Rata-rata, kata Dwi, total kebutuhan kedelai di dalam negeri mencapai 8 juta ton per tahun. Mayoritas atau lebih dari 7 juta ton biasanya dipenuhi lewat impor.
“Sehingga sekitar 90 persen kedelai di Indonesia dipenuhi dari impor,” imbuh Dwi.
Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Sumedang Nandang menyatakan kedelai umumnya cuma menjadi komoditas sampingan untuk ditanam. Mayoritas petani enggan menanam kedelai karena tak mendatangkan banyak keuntungan.
Jumlah produksi kedelai lokal hanya sedikit. Menurut Nandang, petani lebih memilih menanam komoditas lain seperti padi atau ubi karena pasarnya lebih menjanjikan.
“Petani cari yang lebih untung, kalau lebih untung menanam padi kenapa menanam kedelai,” imbuh Nandang.
Dengan demikian, jika pemerintah memperluas areal pertanian untuk kedelai, belum tentu bisa menambah produksi kedelai lokal secara signifikan.
Kalau tambahan lahan tersebut menjadi milik pemerintah dan hanya boleh ditanami kedelai maka produksi bisa meningkat. Namun, apabila lahan tersebut menjadi milik petani maka sulit menambah produksi kedelai.
“Kalau lahan milik pemerintah mungkin (bisa menambah produksi kedelai lokal). Kalau milik masyarakat, mereka akan memikirkan mana yang lebih menguntungkan,” jelas dia.
Di sisi lain, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmaja berpendapat upaya pemerintah untuk menaikkan produksi kedelai lokal dalam 200 hari bisa saja dilakukan. Namun, pekerjaan rumah pemerintah bukan cuma itu.
Pemerintah, kata Entang, juga harus memastikan apakah kedelai lokal diminati atau tidak oleh pasar. Hal ini khususnya oleh pengrajin tahu dan tempe.
“Jadi bukan hanya produksi, tapi setelah produksi laku atau tidak? Sudah ada bukti belum bahwa kedelai itu diminati oleh pengrajin tahu dan tempe,” kata Entang.
Sebab, persoalan utama bukan pada kedelai impor. Tapi kenaikan harga tempe dan tahu akibat peningkatan harga kedelai impor.
Andai saja tak berpengaruh terhadap tahu dan tempe yang menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia, Entang menyebut kenaikan harga kedelai impor tak akan menjadi persoalan besar seperti sekarang. Jadi, pemerintah juga harus bisa memastikan apakah pengrajin tahu dan tempe mau membeli kedelai lokal atau tidak.
“Pastikan apakah pengrajin tempe dan tahu mau atau tidak, mungkin kedelai lokal bisa laku tapi dibeli industri lain. Kalau pengrajin tahu dan tempe tidak beli, belinya tetap kedelai impor, sama saja mahal, persoalan tidak selesai,” papar Entang.
Menurut Entang, pengrajin tempe dan tahu selama ini lebih suka dengan kedelai impor. Pasalnya, kualitas kedelai dari luar negeri jauh lebih bagus ketimbang kedelai lokal.
“Kedelai impor besar-besar. Kedelai lokal kalau mau besar disuntik-suntik dulu, itu tidak efisien karena akan mahal,” terang Entang.
Lagi pula, tak banyak petani yang mau menanam kedelai karena untungnya sedikit. Entang menyatakan 1 hektare cuma bisa menghasilkan 1-2 ton kedelai.
Jika harga kedelai lokal Rp8.000 per kilogram (kg), maka petani bisa meraup pendapatan Rp16 juta ketika panen. Namun, biaya produksinya bisa mencapai 60 persen dari total pendapatan.
“Biaya produksi beli benih, kalau bukan lahan sendiri berarti harus sewa, kalau butuh tenaga kerja harus siapkan upah, pupuk, dan pembersihan lahan harus ada ongkos. Kalau menurut saya biaya produksi bisa 60 persen dari Rp16 juta, jadi sekitar Rp9 juta,” jelas Entang.
Jika petani menaikkan harga kedelai lokal demi meraup untung lebih banyak, maka pengrajin tahu dan tempe semakin tak mau membeli kedelai lokal. Mereka akan lebih memilih kedelai impor yang besar-besar ketimbang kedelai lokal yang bentuknya lebih kecil.
“Kalau menaikkan harga kedelai lokal (agar keuntungan lebih banyak), mahal sama saja seperti yang impor. Jadi ujung-ujungnya akan tetap impor,” ujar Entang.
Menurut Entang, Kementerian Pertanian jangan terburu-buru mendongkrak produksi kedelai lokal. Selain karena pengrajin tahu dan tempe lebih suka kedelai impor, pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor cuaca.
“Kalau La Nina, ada serangan hama penyakit, bahaya. La Nina menyerang seluruh komoditas. Takutnya produksi diserang hama, jadi harus dicermati lagi,” tutur Entang.
Maka dari itu, ia menyarankan Kementerian Pertanian melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai produksi kedelai. Pemerintah harus melibatkan peneliti, tokoh-tokoh perguruan tinggi, dan petani kedelai.
(Bagus)